
Judul Buku: Kasus Ajaib Bahasa Indonesia? Pemodernan Kosakata dan Politik Peristilahan
Penulis: Jérôme Samuel
Penerjemah: Dhany Saraswati Wardhany
Penyunting: Emma Sitohang-Nababan
Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia
Tahun terbit: 2008
Kota terbit: Jakarta
Jumlah halaman: 534
Jika gelombang pemodernan berasal dari luar, masalah utama yang diakibatkan oleh pemodernan sebenarnya adalah masalah pelengkapan kosakata, bagaimanapun prosedurnya. Masalah pemungutan dan purisme tidaklah sepenting seperti yang disiratkan oleh literatur sosiolinguistik.
Pertanyaan pertama yang muncul di kepala saya ketika membaca judul buku ini adalah “[k]enapa pemodernan dan bukan modernisasi? Bukankah kata ‘modernisasi’ lebih dekat dengan para penutur daripada pemodernan? Apakah keduanya sah dipakai? Apakah keduanya baku?” Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya tidak diberikan oleh buku ini secara langsung, tetapi kemudian saya menyadari sejarah atas alasan kenapa begitu banyak model cara pembentukan kata dan istilah dalam bahasa Indonesia, atas menggelembungnya jumlah sinonim dalam bahasa Indonesia.
Buku ini merupakan penelitian sejarah pemodernan kosakata dan politik peristilahan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga resmi kebahasaan di Nusantara. Saya menyebutkan kata Nusantara karena Jérôme Samuel juga meneliti asal-usul kegiatan peristilahan sejak zaman pra-kolonial dan Hindia belanda (meskipun Jérôme Samuel sendiri memakai kata Indonesia secara konsisten untuk menyebut wilayah Nusantara pra-kemerdekaan). Kajian buku ini memang lebih terfokus pada pemodernan istilah di Indonesia pada masa pendudukan Jepang hingga rezim Orde Baru, tepatnya tahun 1995. Pun demikian, penulisnya tetap menjelaskan sejarah peristilahan dan penyerapan kosakata asing dari abad ke-8. Garis besar penyerapan itu ia klasifikasikan sebagai urutan proses, yaitu proses Indianisasi, Islamisasi dan Arabisasi, dan Hindia Belanda. Setelahnya, Jérôme Samuel membagi masa peristilahan menurut beberapa tahap, yaitu Tahap Pertama (Masa Pendudukan Jepang dan periode Soekarno), Tahap Pematangan (1967-1975), dan Orde Baru Peristilahan (1975-1995). Ada lima bagian dalam buku ini dan setiap bagian dibagi dalam bab-bab.
Dalam Proses Indianisasi, dan Islamisasi dan Arabisasi, Jérôme Samuel menelaah ciri-ciri pemungutan kata dan peristilahan untuk menamai konsep-konsep baru yang masuk ke Nusantara. Pada proses Indianisasi, misalnya, pemungutan dilakukan untuk penyerapan, tetapi sering didampingi oleh “pakar-pakar” dari Asia Selatan dan Timur Tengah. Karena peristilahan pada masa Islam masuk tidak ditangani lembaga pemerintahan serta bersifat lebih egaliter, gagasan, teks yang mewadahi, dan istilah-istilah diserap oleh para pelaut, pedagang, dan masyarakat perkotaan. Di proses ketiga, di bawah kekuasaan kolonial, kemajuan bahasa Melayu terhalang oleh perkembangan fungsinya yang terbatas, namun dikuatkan oleh meningkatnya jumlah publikasi tulisan dan bertambah intensifnya hubungan antara pemerintah kolonial dengan masyarakat pribumi. Di proses ini pula penelitian tentang bahasa Melayu tidak bisa tidak memainkan peran penting dalam pengindonesiaan Melayu sebagai bahasa nasional dan kegelisahan atas pentingnya menggunakan bahasa sebagai media pemersatu dan penggerak kebudayaan.
Latar sejarah pemungutan istilah yang panjang adalah alat yang dipakai Jérôme Samuel untuk mengkritik tulisan-tulisan/kajian-kajian sosiolinguistik yang tidak didasarkan pada pemahaman sejarah dan kebudayaan Indonesia.
Penelitian pada Tahap Pertama pemodernan istilah difokuskan pada dua lembaga, yaitu Komisi Bahasa Indonesia (1942-1945) dan Komisi Istilah (1952-1966). Pada tahap ini, semangat kebahasaannya adalah kebangsaan dan kebutuhan untuk menyatakan identitas nasional. Neologisme (kata bentukan baru atau makna baru untuk kata lama yang dipakai dalam bahasa yang memberi ciri pribadi atau demi pengembangan kosakata) yang dipakai oleh kedua lembaga tersebut adalah bahasa Belanda. Komisi Istilah mendapatkan posisi otonom (ditempatkan di bawah perdana menteri), namun tidak terikat dengan kebijakan pendidikan dan tidak memiliki hubungan yang jelas dengan instansi pendidikan. Oleh karenanya, masalah implementasi dan evaluasi ketahanan istilah belum masuk menjadi agenda kerja lembaga. Dalam tahap ini, ada pemungutan istilah besar-besaran yang dilakukan, yaitu ratusan ribu istilah (taksirannya berbeda-beda, ada yang bilang 327.927 istilah dan ada yang bilang hanya sekitar 144.000 istilah).
Tahap Pematangan adalah periode yang dimulai setelah jatuhnya Soekarno dan dimulainya rezim Orde Baru. Tahap ini dinamai Tahap Pematangan karena dari sinilah dimulai kerja evaluatif kinerja KI dan perencanaan yang lebih matang (sistematis) untuk politik bahasa nasional (bisa berarti: politik bahasa nasional [politik bahasa Indonesia] dan politik bahasa nasional [politik nasional dalam bidang bahasa]). Pada tahap ini pula pemikiran sosiolinguistik Amerika mulai bermain penting, yang indikator kuatnya adalah penelitian yang dilakukan oleh lembaga International Research Project on Languange Planning Processes (IRPLPP) atas pendanaan dari Ford Foundation. Peneliti-penelitinya adalah Joan Rubin dan Bjorn Jernudd, yang menggunakan fondasi “perencanaan bahasa” (sebuah sosiolinguistik terapan dengan perhatian utama pada pemecahan masalah-masalah bahasa di negara-negara berkembang, baik dari segi status maupun pembakuan bahasa) yang telah diletakkan oleh “grup Fishman”. Orang-orang baru bermunculan di periode ini, dan yang paling menonjol adalah Amran Halim, Anton M. Moeliono, dan Harimurti Kridalaksana. Pada tahap ini pula, Ejaan Yang Disempurnakan disepakati, yaitu dengan SK Menteri P. dan K. no. 03/A.I/72 tanggal 20 Mei 1972. Di samping itu, struktur-struktur baru kelembagaan mulai terbentuk dan yang akan menjadi landasan bagi tahap berikutnya.
Tahap ketiga adalah Tahap Orde Baru peristilahan. Tahap ini ditandai dengan berdirinya Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa (P3B) pada tahun 1975. Kalangan ahli bahasa periode setelah 1975 didominasi oleh orang-orang yang latar belakang pemahamanan bahasa asing yang dikuasai adalah hanya bahasa Inggris. Oleh karenanya, bahasa Inggris menjadi satu-satunya bahasa sumber bagi para pakar terminologi Indonesia. Produk yang menonjol adalah kamus ekabahasa bilingual. Neologisme resmi P3B mengedepankan pilihan-pilihan seperti pemungutan Melayu atau Nusantara dan penggunaan bentuk-bentuk yang rumit (afiksasi kompleks, menjawab kebutuhan kebahasaan untuk elit pemimpin. Sedangkan pada proses kedua, kaum elit berperan aktif dalam peristilahan dan penggabungan klasik). Dalam kerjanya, P3B juga lemah di implementasi dan publikasi peristilahan karena publiknya homogen: dosen dan peneliti.
Masih seperti masalah klasik yang ada, yaitu keliaran berbahasa penutur dan lembaga pembaku istilah, peristilahan yang dilakukan P3B tidak memerdulikan penutur dan kebiasaan yang berlaku. Akibatnya, produk P3B menggelembungkan persediaan istilah dari jumlah sinonim, sementara yang diperlukan sebenarnya adalah meregulasi penawaran yang melimpah dan tidak menguntungkan bagi kelancaran komunikasi. Sementara itu, perbedaan utama KI dan P3B terletak pada kekuasaan akhir atas pembakuan istilah. Jikalau dalam KI kekuasaan berada di tangan para ahli bahasa, di P3B ahli bahasa menyerahkan posisi mereka pada para pakar bidang ilmu. (Pantas saja penyusunan redaksional Undang-undang saja bisa ambigu/taksa penafsirannya).
Kajian lain dalam buku ini adalah deskripsi dan evaluasi terhadap kerjasama internasional (peristilahan dalam kerangka Malayofoni) yang ditandai dengan kelahiran MABBIM (Majelis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia), dan pengujian Peristilahan Resmi tahun 1975 sampai 1995, khususnya di bidang Elektromagnetika, serta Peristilahan resmi dan implementasinya di sekolah, khususnya bidang Termodinamika.
Buku yang cukup tebal ini sangat cocok bagi orang yang ingin memahami gejala peristilahan yang silang-sengkarut dan centang-perenang dalam bahasa Indonesia. Yang cukup mengejutkan dari buku ini, ketika membaca sejarah peristilahan di Indonesia, menurut saya, adalah fakta bahwa faktor luarlah yang paling banyak mempengaruhi perubahan kosakata dan politik peristilahan di Indonesia (dari Indianisasi hingga politik bahasa nasional). Juga, bahwa bahasa, khususnya sejak dibiayai oleh Ford Foundation, tidak lain dan tidak bukan merupakan ranah implementasi dari sebuah skema besar yang sistematis untuk mefondasikan kajian-kajian linguistik kebahasaan di Indonesia pada penelitian-penelitian Amerika, yang efek jangka panjangnya sangat mengerikan.
Pernyataan saya terlihat sangat politis. Namun, demikianlah kesan yang saya dapat dari buku ini meskipun Jérôme Samuel tidak secara rinci menjabarkan efek politis dari pendanaan Ford Foundation. Pun demikian, ia tetap memberikan catatan kaki bahwa “perlu dilakukan penelitian mendalam tentang kegiatan dan pengaruh Ford Foundation yang sudah aktif sejak beberapa dasa warsa terakhir. Setelah pergantian rezim 1965-1966, melalui program penelitian dan kegiatan sosialnya, melalui beasiswa yang diberikannya, yayasan swasta Amerika ini tidak sedikit sumbangannya dalam membentuk kalangan elite cendikiawan Indonesia yang mengamerika dan mendukung prinsip-prinsip Orde Baru. Kegiatan yayasan ini dalam bidang politik bahasa merupakan salah satu aspeknya.” Nah, jangan-jangan, pilihan kita sekarang tinggal dua: “Pengamerikaan” atau “Amerikanisasi”? Tentu saja bukan itu yang ditekankan oleh buku karangan Dr. Jérôme Samuel, pengajar INALCO, institut yang mengajarkan Bahasa dan Kebudayaan Timur di Paris ini. Silahkan baca sendiri untuk mendapatkan kesan lain yang membekas di hati Anda.
*Ulasan ini sebelumnya terbit di Majalah Bahasa Lidahibu #6, 28 Oktober 2009 dan situsweb lidahibu.com
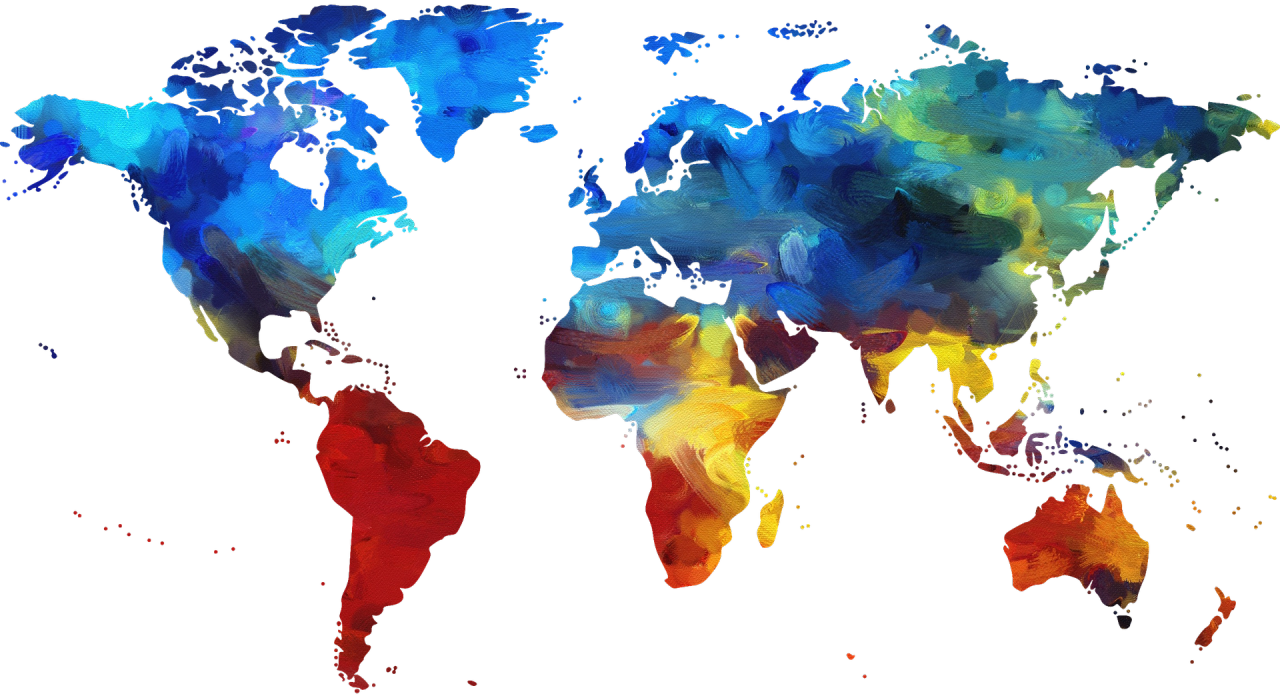
Tinggalkan Balasan