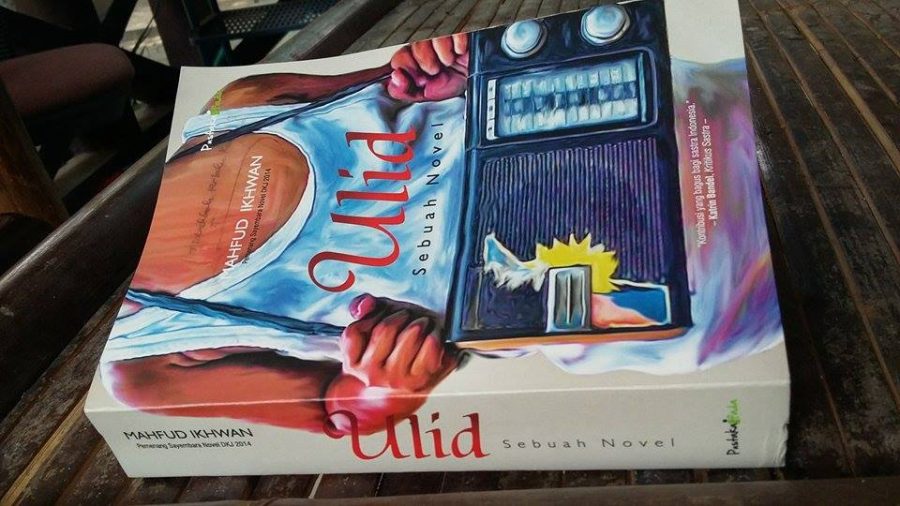Saya mungkin adalah salah satu pembaca yang dibayangkan Mahfud Ikhwan di saat-saat awal menulis Ulid. Saya orang desa yang hidup di kota dan masih “ndeso”. Desa saya, seperti desa-desa jutaan anak Indonesia yang lahir pada tahun 1970an-1980an, memiliki dinamika yang mirip dengan Lerok-nya Ulid: diselimuti kemiskinan dan mengalami goncangan dahsyat karena perubahan mata pencaharian sebagian besar masyarakatnya. Karenanya, kenikmatan utama yang muncul dari membaca Ulid adalah identifikasi ‘kedesaan’—pengalaman masa kecil dan remaja di desa, pengalaman menghadapi perubahan besar, dan pengalaman pergi dari desa.
Bulan: April 2017
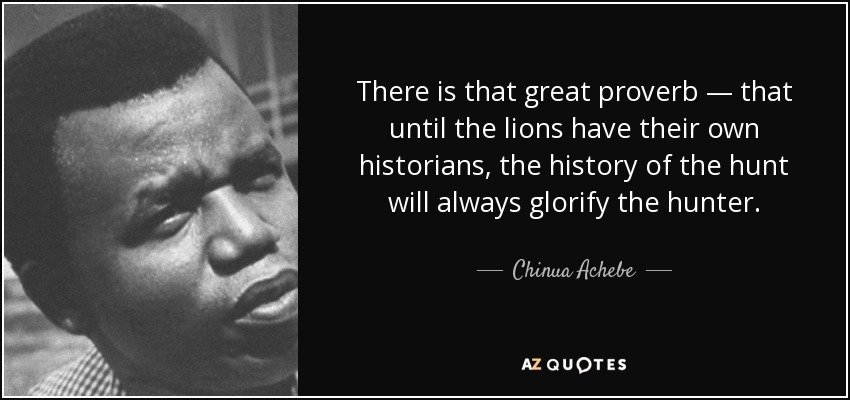
Di antara sekian banyak sastrawan ternama Nigeria, Wole Soyinka dan Chinua Achebe bisa dianggap sebagai yang paling terkenal dan berpengaruh, baik di dalam negeri maupun internasional. Di Indonesia, posisi mereka bisa kita sejajarkan dengan WS Rendra dan Pramoedya Ananta Toer. Keempat sastrawan tersebut, dengan caranya masing-masing, banyak mengeksplorasi kondisi keterjajahan negerinya dan memberi pengaruh pada cara pandang terhadap identitas masyarakatnya. Eksplorasi seperti yang mereka lakukan itulah yang kemudian melahirkan sebuah disiplin akademis bernama Kajian Pascakolonial pada awal dasawarsa 1990an. Tepatnya, eksplorasi macam apa yang dilakukan oleh mereka dan banyak sastrawan, seniman, dan intelektual lain sehingga bisa melahirkan satu disiplin akademis tersendiri? Tanpa mengesampingkan peran yang lain, pertanyaan itu akan coba saya jawab dengan mendekati tulisan-tulisan Chinua Achebe dan memfokuskannya di bidang sastra—awalnya, isu-isu dalam kajian ini memang muncul dari sastra.

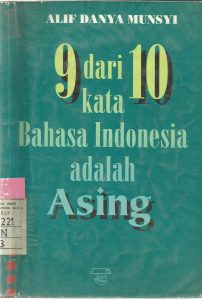
Penulis : Alif Danya Munsyi
Edisi : Pertama
Penerbit : Pustaka Firdaus
Kota terbit : Jakarta
Tahun terbit : 1996
Tebal buku : 134 halaman
Adalah Pusat Bahasa, atau yang dulu bernama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B), yang paling gencar menyuarakan paradigma ‘bahasa Indonesia yang baik dan benar”; sebuah paradigma preskriptivisme (berupa resep) yang diajukan dan dipaksakan untuk dipatuhi oleh para penutur Bahasa Indonesia. Ideologi nasionalisme-paksa ini, selain tak pernah berhasil diterapkan, juga menjadi tanda bagi ketuna-sejarahan para ahli bahasa perumusnya akan lalu lintas kata dan istilah dalam bahasa Indonesia.